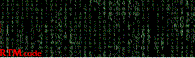Pada dasarnya Ospek merupakan wahana sosialisasi kampus bagi mahasiswa baru sehingga ada semacam pengetahuan dan pengalaman awal agar setelah masuk secara total tidak mengalami kegrogian. Dalam Ospek itu pulalah maba dibekali wawasan secara ideal, apa dan bagaimana sesungguhnya makhluk yang bernama mahasiswa itu. Agar mereka lebih mengenal dirinya, dapat mengaktualisir diri secara merdeka. Begitupun jika melihat jargon-jargon yang dikemas secara teoritik maka Ospek sesungguhnya sesuatu yang ideal karena penuh dengan pemberdayaan, penuh idealisme, penuh aroma intelektual sampai dibumbui dengan slogan ’Ilmiah dan Religius’. Namun, sayang dalam banyak kejadian Ospek harus dikritik, apalagi jika dipandang dari sudut paedagogis. Karena ternyata Ospek kering dengan pendekatan humanistik. Perangkat dan aturannya bersifat memaksakan sehingga tidak ada ruang sedikitpun bagi maba untuk berkreativitas. Ditutupnya ruang dialog dan komunikasi yang seimbang menyebabkan wajah Ospek begitu sangat buram, stagnan dan sangat mengerikan.
Bukti kengerian itu dapat dilihat dari pengalaman Ospek di tahun-tahun sebelumnya. Di UNDIP Semarang, Sivino Amaral meninggal dunia disebabkan kerasnya pelaksanaan Ospek. Andri Setiaji (masih di UNDIP) punya cerita yang menimbulkan ketraumaan psikologis yang luar biasa, ia dikeroyok 20 mahasiswa senior karena dinilai membantah dan memprotes para seniornya. Begitupun dibeberapa perguruan tinggi di pelosok tanah air tiap tahunnya memakan korban. Saya yakin kematian Wahyu Hidayat masih akan tetap membekas di benak kita semua. Dan Wahyu bukan korban pertama. Kekerasan menjadi budaya di Sekolah Tinggi yang siswanya kelak menjadi abdi negara. Gaya ’komando’ untuk mendisiplinkan menjadi sebuah keladziman. Kekerasan pun berbuah kematian, stress bahkan ada yang hampir gila. Karenanya tidak salah jika beberapa media menyebut STPDN sebagai Sekolah Tukang Pukul Dalam Negeri. Atau yang lebih sangar lagi, Mingguan Tempo menjulukinya ’neraka’.
Berbagai kejadian riil di lapangan itulah yang selalu menimbulkan perdebatan yang tak kunjung usai. Ada yang menginginkan Ospek dihapus sama sekali karena hampir setiap Ospek selalu menimbulkan korban mulai dari cacat fisik yang ringan hingga yang cukup parah, bahkan tak jarang korbannya mengalami trauma psikologis yang berkepanjangan dan tak sedikit yang tewas akibat kebrutalan Ospek.
Dipandang dari sudut manapun, dengan model Ospek yang stagnan dan itu-itu tonji penulis menilai adalah sesuatu yang absurd. Pemandangan peserta Ospek yang ditampilkan kekanak-kanakan, lucu, menggemaskan sekaligus menimbulkan rasa iba menimbulkan satu pertanyaan untuk apa semua itu dilakukan ?. Imbasnya hanya satu, menimbulkan bahan tertawaan orang, tak ada sangkut pautnya dengan nilai-nilai intelektualitas, ilmiah apalagi religiusitas. Apalagi secara ekonomi, seluruh atribut yang dibebankan kepada maba menjadi beban yang semakin memberatkan. Mereka sudah harus membayar berbagai keperluan kampus, masih harus menanggung biaya Ospek. Dari sini terlihat secara jelas kesenjangan yang terjadi. Bila kita menyakini Ospek merupakan masa orientasi yang terjadi justru penetrasi kehendak. Bila kita menilai Ospek merupakan sarana pengenalan kampus yang terjadi masa ketakutan terhadap lingkungannya. Ospek diinginkan sebagi proses pendidikan yang terjadi justru praktik penindasan yang dahsyat. Lewat Ospek, kampus kehilangan nafas intelektual, ilmiah apalagi religius, misi kerakyatan dan pemihakan pada kaum tertindas pudar, idealisme larut. Karena yang hadir justru iklim kekerasan dan penindasan. Ini berarti terjadi negasi besar-besaran. Kita (para senior) bisa jadi terjebak dalam situasi yang paradoks. Kebebasan akademik yang dituntut selama ini justru diberangus saat Ospek. Pendidikan yang memanusiakan yang diperjuangkan sepanjang masa oleh mahasiswa diinjak-injak sendiri dalam prosesi Ospek. Pemihakan kepada mereka yang kesulitan membayar uang kuliah terlupa sesaat. Oleh karenanya selama Ospek menjadi instrument pemasungan dan penindasan mahasiswa baru oleh mahasiswa lama, maka selama itu pula Ospek layak digugat.
Sebagai wahana pengenalan kampus kepada maba yang masih ’lugu’ , maka Ospek bagaimanapun tetap dibutuhkan. Hanya saja diperlukan kebesaran jiwa para panitia Ospek untuk mengejawantahkan slogan-slogan penyambutan yang dibuat ke ’lapangan’, dan menghilangkan frame bahwa tindakan tidak manusiawi (bahasa kasarnya :pembinatangan) dalam Ospek harus dipertahankan. Haruskah superioritas, penindasan, otoritas, dan tindakan subversif lainnya kembali terjadi, haruskah itu mentradisi padahal tidak ada yang nyuruh ? . Apa salahnya kalau kita menyiapkan ruang penyambutan yang berintikan pembebasan kesadaran atau dialogika, yakni memancing mereka untuk berdialog, membiarkan mereka mengucapkan sendiri perkataannya, mendorong mereka menamai dan dengan demikian merubah paradigma mereka tentang dunia yang bisa saja selama ini meleset. Kita harus sadar yang kita hadapi adalah manusia-manusia yang butuh kesadaran, hendak disentak kemanusiannya, tapi seringkali kita masih tetap terjebak pada prosesi Ospek dengan kreativitas itu-itu juga. Hasilnya kita justru mengkader jiwa-jiwa penindas. Irrasionalitas, immoralitas, dan agresivitas adalah buah dari pohon yang kita tanam sendiri. Kita (mahasiswa senior) mesti berpikir, bahwa maba adalah adik yang akan mencontoh kakak-kakaknya dan hendaknya lebih menekankan pada maba akan penguatan dan pematangan nalar, bukan semata fisik. Bagaimanapun maba adalah manusia juga. Manusia yang memiliki keinginan untuk mencari dan mendekati Allah sebagai kodrat pertamanya sebagai manusia. Karenanya bantu mereka untuk merealisasikan keinginannya yang paling purba itu. Mencari, mendekati dan mencintai Allah Subhanahu wata ala.
Mari bekerjasama.
Ismail Amin Mahasiswa Mostafa International University Republik Islam Iran
Dimuat di Tribun Timur, 1 September 2009