(Tanggapan atas tulisan Adi Wijaya yang berjudul:
Pemilihan Pemimpin dalam Sistem Islam)
Saya mengawali tulisan ini dengan berharap, jangan diartikan bahwa saya berupaya merusak keyakinan mayoritas kaum Muslimin yang telah mengakar. Tanggapan untuk tulisan Adi Wijaya ini berbentuk sejumlah pertanyaan yang telah mengganggu saya sejak lama.
Diantaranya, kalau keberadaan seorang pemimpin dalam ajaran Islam adalah wajib dan urgen adanya, mengapa Rasulullah SAW tidak sejak awal menetapkan siapa yang akan yang akan memimpin umat yang akan ditinggalkannya?. Atau minimal memberi petunjuk yang jelas mengenai prosedur memilih dan mengangkat pemimpin?. Baiat bukanlah metode pemilihan dan pengangkatan pemimpin atau kepala negara, melainkan pengakuan atas kredibilitas orang yang terpilih sebagai pemimpin dengan memberikan ketaatan dan loyalitas kepadanya. Secara terminologi, baiat diartikan, berjanji untuk taat, bukan metode pemilihan atau pengangkatan. Jika kita merujuk pada empat khalifah awal pasca Rasulullah SAW, setidaknya ada empat metode yang berbeda dalam pengangkatan khalifah. Abu Bakar terpilih dari kesepakatan sebagian kecil kaum muslimin di Saqifah, Umar bin Khattab dibaiat sebagai khalifah selanjutnya sesuai dengan petunjuk dan pilihan 'secara sepihak' oleh Abu Bakar. Sebelum wafat, Umar bin Khattab membentuk dewan pemilihan yang terdiri atas enam sahabat terkemuka, dan dari pembincangan tersebut terpilihlah Usman bin Affan. Ali bin Abi Thalib menjadi khalifah selanjutnya melalui ijma (konsensus) kaum muslimin, tanpa melalui sedikitpun prosedur pemilihan. Sementara Muawiyah bin Abu Sufyan mendapatkan pengakuan sebagai khalifah dengan terlebih dahulu menebar teror dan upaya kudeta berdarah.
Saya benar-benar tidak bisa menerima kenyataan ini, bahwa Rasulullah SAW meninggalkan Daulah yang masih berumur muda dengan tidak sedikitpun petunjuk untuk menjaga kelestarian dan keutuhannya, seakan-akan Rasulullah Saw bersikap pasif terhadap masa depan dan kelanjutan misi dakwah. Rasulullah SAW menyampaikan kepada umatnya, ada tiga hal yang tidak boleh ditunda pelaksanaannya, salah satunya adalah pemakaman jenazah setelah dimandikan. Namun jenazah mulia Rasulullah SAW dibiarkan menunggu selama tiga hari. Ijtihad ataupun ijma sahabat tidak bisa dibenarkan ketika berhadapan dengan nash yang jelas. Dan nashnya sangat jelas bahwa wajib untuk tidak menunda pemakaman, terlebih lagi jika jenazah itu adalah Rasulullah SAW. Ali bin Abi Thalib ra (diantaranya yang disebut Nabi mendapat jaminan surga) baru melalukan pembaiatan atas Abu Bakar setelah 6 bulan berlalu dari pengangkatannya, Husain bin Ali (disebut Nabi sebagai penghulu pemuda surga) justru lebih memilih dibantai dari pada membaiat Yazid sebagai khalifah, lantas dari mana dapat disimpulkan bahwa kaum Muslimin hanya diberi jeda selama dua hari untuk membaiat seorang khalifah?.
Bila kita beranggapan bahwa Nabi telah meninggalkan umat Islam dengan tanpa terlebih dahulu mempersiapkan rancangan dan agenda kerja yang matang serta menetapkan pengganti yang akan yang melanjutkan misi Ilahiah, maka segala keguncangan dan pertikaian berdarah yang terjadi pasca wafat Rasulullah SAW akan menjadi tanggungjawab beliau. Akan timbul keraguan akan profesionalitas dan kredibilitas Muhammad sebagai seorang pemimpin yang akan berefek pada gugatan atas kenabian beliau. Bila kita sisipkan faktor oknum-oknum (kaum munafikin) yang bersebaran di Madinah maka ini akan mempertegas lagi ketidakmungkinan itu. Logiskah Rasulullah SAW meninggalkan umatnya 'begitu saja' sementara Allah SWT berfirman, "Dan diantara orang-orang Arab yang (tinggal) di sekitarmu, ada orang-orang munafik. Dan di antara penduduk Madinah (ada juga orang-orang munafik), mereka keterlaluan dalam kemunafikannya. Engkau (Muhammad) tidak mengetahui mereka, tetapi Kami mengetahuinya…"(Qs. At-Taubah: 101). Tidakkah Rasulullah SAW khawatir akan kerja-kerja licik orang-orang munafik (yang sulit dikenali) yang bisa saja meruntuhkan Daulah yang telah dibangunnya bersama sahabat-sahabat setianya?. Kekhawatiran inilah yang membuat Abu Bakar harus memilih sendiri Umar bin Khattab sebagai penggantinya, begitu juga dengan Umar bin Khattab yang masih sedikit lebih bijak dengan terlebih dahulu membentuk Dewan Syuro. Bahwa Rasulullah SAW tidak menetapkan sendiri penggantinya ataupun tidak sedikitpun memberi petunjuk mengenai metode pengangkatan pemimpin adalah salah satu versi sejarah, yang sayangnya lebih banyak diakui dan diyakini kaum muslimin sebagai realitas sejarah yang tak bisa ditolak.
Wasiat yang Diabaikan
Dengan renggang waktu teramat singkat -hanya kurang lebih 10 tahun di Madinah- secara psikologis pada dasarnya, kaum muslimin saat itu belum siap ditinggalkan oleh Rasulullah SAW. Tidak heran, jika salah seorang sahabat kawakan ketika mendapat kabar meninggalnya Rasulullah dengan hunusan pedang berteriak, "Rasulullah belum mati! Rasulullah tidak akan mati! Siapa yang mengatakan beliau mati akan saya penggal!". Ya, tentu saja ketidaksiapan ini telah menjadi pertimbangan Rasulullah SAW yang dimasa-masa kritisnya bersabda, ""Berikan padaku selembar kertas dan tinta. Aku tuliskan untuk kalian semua sebuah wasiat yang jika kalian mematuhi isinya, niscaya kalian tidak sesat setelah aku tinggal pergi." (Riwayat Bukhari-Muslim).
Sebenarnya apa yang dilakukan oleh Rasul pada detik-detik yang paling mendebarkan di akhir hidupnya adalah bukti akurat yang menolak mentah-mentah versi sejarah pertama sekaligus merupakan gambaran yang cukup jelas bahwa Rasulullah SAW bukanlah orang yang tidak peduli akan prospek dan nasib dakwah. Sayangnya permintaan Rasulullah untuk menuliskan wasiatnya tidak diindahkan dengan ucapan salah seorang sahabat, "Nabi telah makin parah sakitnya, sedangkan Al-Qur'an ada pada kalian. Cukuplah kitab Allah bagi kita !". Kedua, adanya upaya melupakan wasiat Rasulullah yang disampaikan menjelang wafatnya. Lihat saja, petikan hadits dalam Shahih Muslim bab al-Washiyah, Ibnu Abbas berkata, “Dan beliau (Rasulullah) mewasiatkan menjelang wafatnya,’ Keluarkan kaum musyrikin dari Jazirah Arab dan beri hadiah kepada utusan sebagaimana yang aku lakukan !’ (perawi hadits ini melanjutkan) Dan aku lupa yang ketiga”. Sulit menerima bahwa mereka lupa apalagi ini wasiat nabi yang berkaitan dengan masa depan ummat. Namun demikianlah kenyataannya, dan inilah yang terjadi. Dalam perjalanan selanjutnya, aturan politik dan kepemimpinan dalam Islam terpecah menjadi kepingan-kepingan besar. Sebagian besar umat Islam menyatakan Islam tidak mengurusi persoalan politik, dan sebagiannya lagi justru sibuk menggedor-gedor kesadaran kaum muslimin akan pentingnya politik dan kekhilafaan dalam masyarakat Islam.
Terakhir, saya bertanya, benarkah dalam perspektif syariat Islam kondisi masyarakat -saya menyebutnya konteks sosial- bukanlah dasar untuk menentukan status hukum suatu perkara?. Benarkah realitaslah yang harus diubah agar sesuai dengan syariat Islam, dan bukan sebaliknya?. Dalam Ushul Fiqh ada kaidah yang sangat terkenal, “taghayyur al-ahkam bi taghayyur al-azminati wa al-amkan,” hukum bisa berubah sesuai dengan waktu dan tempat (baca: sesuai dengan kondisinya). Seorang muslim yang tidak mampu sholat sambil berdiri, maka syariat membolehkan untuk duduk, jika masih sulit juga, maka diizinkan baginya sholat sambil berbaring. Daging yang diharamkan bisa menjadi halal ketika diperhadapkan pada konteks tidak ada lagi yang bisa dimakan dan berkaitan dengan kelangsungan hidup. Syariatlah yang menyesuaikan diri dengan realitas, bukan sebaliknya. Ketika belum ada yang layak dibaiat menjadi khalifah maka lahirkanlah dulu calon-calon khalifah. Tidak serta merta kita semua menjadi pendosa hanya karena teks agama mengatakan, baiat adalah kewajiban yang tidak bisa ditawar-tawar lagi. Bukan begitu?.
Wallahu 'alam bishshawwab
Ismail Amin
Qom, 22 Maret 2009
NB:
Tulisan di atas juga bisa dibaca di http://www.tribun-timur.com/read/artikel/19005
Tulisan Adi Wijaya di muat di Tribun Timur 20 Maret 2009 selengkapnya di http://www.tribun-timur.com/read/artikel/17733










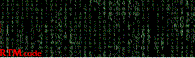

1 komentar:
tulisan yg inspiratif
Posting Komentar