Pekan ini, hari terakhir anak-anak sekolah menghabiskan masa liburannya. Sedangkan bagi anak-anak yang baru didaftarkan, ini adalah hari terakhir mereka tidak harus dibangunkan terlalu pagi, untuk mandi, sarapan dan berseragam. Pengalaman hari pertama masuk sekolah bagi anak bisa jadi merupakan peristiwa penting yang sulit dilupakan. Ada kesan kegembiraan yang meluap disana, karena sekolah sejak awalnya menawarkan kegembiraan dengan teman-teman yang dapat diajak bermain-main dan menjanjikan pengalaman baru yang belum pernah dialami sebelumnya. Bagaimanapun juga, persiapan menjelang hari pertama masuk sekolah merupakan kesibukan tersendiri baik bagi orangtua terlebih lagi bagi sang anak. Hanya saja yang menjadi persoalan berikutnya adalah, benarkah selama ini sekolah berperan sebagaimana seharusnya bagi perkembangan pendidikan sang anak ?. Pertanyaan ini harus menjadi refleksi bagi para orangtua, agar tidak terjebak pada rutinitas menghantarkan anak ke sekolah, yang bisa berakibat fatal jika tanpa disertai kesadaran. Sebab tidak menutup kemungkinan, kita bukannya mengantar anak ke sekolah tetapi (maaf) malah membuangnya ke bak sampah. Saya tuliskan ucapan Everet Reimer, “Nenek ingin saya memperoleh pendidikan, karenanya, ia tidak mengizinkan saya sekolah” untuk menemani kita melakukan perefleksian ulang.
Persoalan Dasar Dunia Persekolahan Kita
Anak harus disekolahkan, idealnya memang seperti itu. Sebab fakta bahwa tak satupun keluarga yang mampu mendidik, mengajar dan melatih anak-anak mereka tanpa bantuan ‘orang sekampung’ (meminjam istilah Hillary Rodham Clinton). Pendidikan bagi anak menuntut adanya pembagian peran, tugas dan tanggung jawab dalam masyarakat. Dan dalam perspektif itulah lembaga-lembaga pengajaran atau dunia persekolahan (mulai dari tingkat dasar hingga perguruan tinggi) diberi tugas untuk membantu atau menerima sebagian tanggungjawab tersebut dan bukan seluruhnya, guna menolong orangtua agar dapat menjalankan peran mereka secara lebih bertanggungjawab. Hanya saja, realitas yang terjadi sebagian besar orangtua, mendidik anak itu berarti mempersiapkan uang sekolah, membelikan seragam, buku-buku dan perlengkapan belajar lainnya. Tanpa selanjutnya mau peduli dengan kondisi pendidikan anaknya dan menyerahkan sepenuhnya kepada lembaga formal tersebut. Kalaupun anaknya mengeluh sulit belajar, orangtuapun memanggil dan membayar mahal guru-guru privat untuk memastikan anak-anaknya mendapatkan nilai tinggi di sekolah.
Fakta inilah yang menyebabkan sekolah dan universitas terjebak pada semacam arogansi, sikap percaya diri yang terlalu berlebihan. Adanya ketergantungan orangtua yang sangat terhadap sekolah menyebabkan sekolah merasa mampu melakukan segalanya asal dibayar. Dengan berbagai ilusi konsep-konsep semacam ‘sekolah unggul’, alumninya diperhitungkan dilingkup nasional bahkan internasional dan lainnya, sekolah merasa wajar melakukan pungutan sebannyak-banyaknya kepada orangtua murid. Inilah sebabnya di Indonesia –sebagaimana yang dikatakan Andreas Harefa (2001)l- sulit membedakan antara sekolah terbaik dengan sekolah termahal.
Apa yang Terjadi dalam Kelas ?
Hampir selama beberapa generasi, proses pendidikan yang dijalankan tidak lebih dari sekedar pengalihan informasi dari guru ke murid secara sepihak. Anak didik dibebani dengan berbagai hapalan teori maupun rumus-rumus, sekedar untuk bisa menjawab soal-soal ujian tapi kemudian sulit diejawantahkan ke dalam realitas sosial. Anak didik hanya memainkan peran pembantu, sebab guru adalah aktornya, pelajar hanya akan menjadi pelengkap penderita yang lebih diperlakukan sebagai obyek ketimbang subyek. Proses pendidikan semacam ini menurut Chaedar Alwasih (1993;23) hanya berfungsi untuk ‘membunuh’ kreativitas murid, karena lebih mengedepankan verbalisme. Verbalisme merupakaan suatu asas pendidikan yang menekankan hapalan bukannya pemahaman, mengedepankan formulasi daripada substansi, parahnya lebih menyukai keseragaman bukannya kemandirian serta hura-hura klasikal bukannya petualangan intelektual. Model pendidikan demikian oleh Paulo Freire dikritik sebagai banking education, hubungan antara guru dengan murid sangat hirearkis dan bersifat vertikal; bahwa guru bicara, menjelaskan dan memberi contoh sementara murid menjadi pendengar saja.
Tidak banyak yang sadar bahwa dengan model pendidikan yang menjadikan murid semata-mata sebagi obyek adalah bentuk kekerasan dan pelanggaran terhadap anak. Pendidikan gaya bank menghalalkan dipakainya kekerasan untuk menertibkan dan mengendalikan para murid. Murid dibelenggu dan ditekan untuk mematuhi apapun perintah dan anjuran pendidik. Kesadaran individu dikikis habis dan mengggantinya dengan kesadaran kolektif yang seragam. Efeknya memunculkan kepribadian yang mekanik, mirip dengan benda mati yang kehilangan kebugaran dan kreativitas (Eko Prasetyo, 2004) dari sinilah proses pembinatangan (bahasa halusnya dehumanisasi) terjadi. Kita dapat saksikan bagaimana nasib anak-anak yang sekarang waktu yang seharusnya diisi dengan permainan dan kegembiraan ditelan untuk belajar, menghapal, memahami dan mengerti berbagai paket pengetahuan, dari pagi hinga sore mirip pekerja pabrik menghabiskan waktunya di ruang kelas untuk menelan pelajaran yang dalam banyak hal tidak menyenangkan. Anak-anak diajarkan pada cara bagaimana ia bisa naik kelas, lulus dan lalu bisa dapat kerjaan. Mereka semata-mata diajarkan cara berhitung dan bukan tentang apa yang seharusnya diperhitungkan. Seorang peneliti pendidikan menulis di harian KOMPAS menurut temuannya rata-rata setiap murid SD kelas 3 sampai kelas 6 dalam setiap kuartal mempelajari sejumlah buku yang ketika ditimbang beratnya 43 kilogram, melebihi berat badan murid SD sendiri. Proses pendidikan yang seharusnya, sebagaimana makna sejatinya yakni menggiring keluar atau membebaskan potensi kemanusiaan yang ada dalam diri setiap individu belumlah terwujud. Yang ada justru pendidikan yang hanya menghasilkan airmata (Shindunata,2000).
Betapa kita merindukan suasana sekolah yang didalamnya pertemuan antara guru dan murid terjadi dalam susana yang demokratis, dimana kecintaan guru terhadap murid-muridnya tak kalah dengan kecintaan ibu kepada anak kandungnya, guru bukan lagi figur yang hanya memberikan suapan bahan pelajaran tetapi teman yang menemani suka duka kehidupan murid. Sebab, kita percaya, sekolah dibangun untuk mengabdikan suatu pengalaman yang tidak lekang oleh waktu. Di sana, diperoleh pengalaman yang menakjubkan sekaligus mengharukan. Sekolah sesungguhnya adalah institusi yang menyenangkan, tempat mengembangkan mental juara dan menemukan jati diri, ranah kreativitas yang mengabulkan impian-impian indah dan membawa para anak didik semakin mendekati Tuhannya. Bukannya sekolah yang memunculkan anak yang tiba-tiba bunuh diri. Kalau realitasnya masih seperti itu, perlukah anak-anak kita sekolahkan ?. Wallahu 'alam bishshawwab
Qom, 10 Juli 2008/ 20 Tir 1387 HS










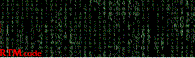

Tidak ada komentar:
Posting Komentar